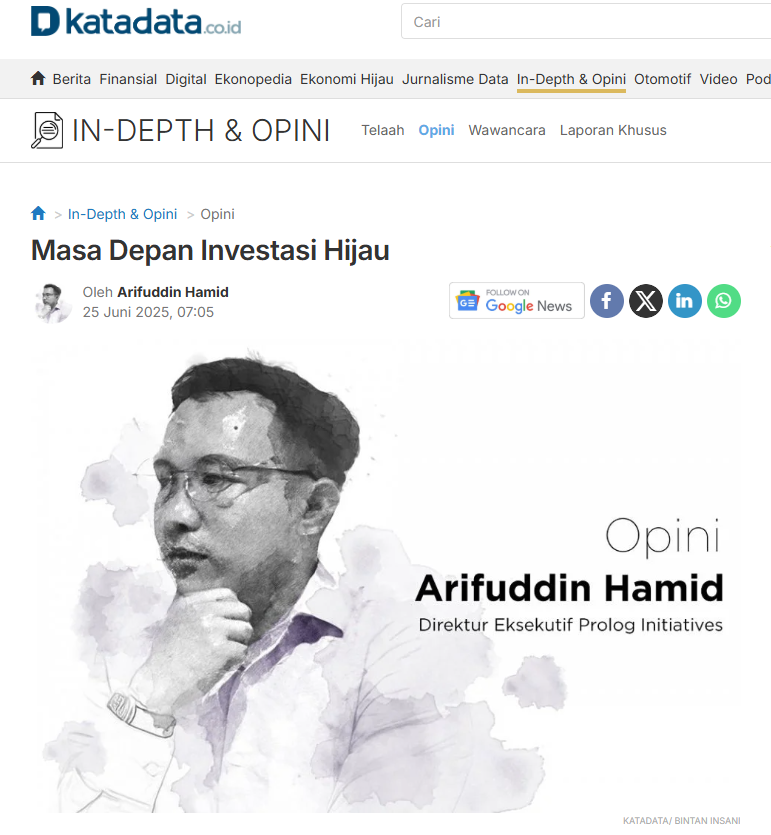 Laporan capaian investasi yang dirilis Kementerian Investasi/BKPM kembali memantik asa ekonomi bangsa. Pada kuartal pertama 2025, realisasi investasi mampu menembus Rp465,2 triliun atau setara 24,4 persen dari total target investasi sebesar Rp1,905,6 triliun. Angka ini sejatinya menggambarkan lajur terarah kinerja investasi. Jika tren ini mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi, maka ada segenggam harapan atas ekonomi global yang serba tidak pasti.
Laporan capaian investasi yang dirilis Kementerian Investasi/BKPM kembali memantik asa ekonomi bangsa. Pada kuartal pertama 2025, realisasi investasi mampu menembus Rp465,2 triliun atau setara 24,4 persen dari total target investasi sebesar Rp1,905,6 triliun. Angka ini sejatinya menggambarkan lajur terarah kinerja investasi. Jika tren ini mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi, maka ada segenggam harapan atas ekonomi global yang serba tidak pasti.
Dari beragam elemen pembentuk pertumbuhan, investasi barangkali menjadi pijakan paling realistis untuk menopang perekonomian. Dinamika perang tarif yang berdampak pada melemahnya ekspor manufaktur dan komoditas mineral semakin menegaskan perlunya peningkatan porsi investasi. Begitu juga dengan melemahnya daya beli masyarakat, harapan untuk menggenjot pertumbuhan semakin menemukan alasan pembenarnya. Maka, dengan postulat resiprokal ini, investasi perlu dijadikan sebagai panglima pertumbuhan.
Namun ada pertanyaan yang pantas diajukan: apakah investasi kita selama ini telah berjalan pada arah yang tepat?
Pertanyaan ini kian relevan karena investasi (mungkin) menyelip eksternalitas negatif, yakni berupa merosotnya keberlanjutan lingkungan dan pemerataan. Dus, investasi yang baik sejatinya sejalur dengan lingkungan yang tetap asri, serta akses inklusif rakyat.
Relevansi Investasi Hijau
Hal paling mendasar adalah mendefinisikan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan investasi hijau? Lalu sejauh mana investasi itu dikatakan hijau? Secara konseptual, definisi investasi hijau punya pemaknaan yang luas. Namun secara umum investasi hijau merujuk pada investasi yang rendah karbon, berketahanan iklim, atau spesifik berfokus pada perubahan iklim (Inderst, 2012). Investasi disebut hijau jika mencakup tiga komponen, yakni penyediaan energi rendah emisi; efisiensi energi; dan penangkapan/ penyimpanan karbon (Eyraud, dkk, 2011).
Diksi investasi hijau mendapatkan relevansi baru paska kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan menegaskan kembalinya penggunaan energi fosil dan keluar dari Kesepakatan Paris, Amerika Serikat menabuh genderang perang terhadap keberlanjutan lingkungan. Menampilkan teatrikal ekonomi yang beraras pada skeptisme ekologis.
Bagi Indonesia, dinamika ini perlu dilihat sebagai peluang baru menuju negara yang punya empati ekologis. Oleh karena itu, merumuskan peta jalan investasi hijau adalah takdir sejarah yang perlu diambil. Indonesia harus punya independensi, bersama dengan negara-negara sepaham, terus maju membela keberlanjutan lingkungan. Investasi yang meminggirkan hak lingkungan adalah deviasi dalam kebijakan publik.
Bagi pemerintahan baru, keberhasilan merawat persenyawaan ekonomi dan ekologi akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Hal ini beralasan sebab World Population Review (2024) mencatat Indonesia menjadi negara ke-2 di dunia dengan tingkat deforestasi terparah. Temuan ini sejalan dengan Auriga Nusantara (2025), deforestasi Indonesia pada 2024 teridentifikasi seluas 261.575 hektare. Dengan bahasa lain, kondisi lingkungan telah menuju level kritis.
Padahal, kerusakan lingkungan bukan sebatas persoalan domestik. Rusaknya hutan di Indonesia akan berdampak pada memburuknya kualitas lingkungan di negara lain, terjadinya krisis iklim, hingga ancaman nyata kehidupan umat manusia. Maka itu, berbagai inisiatif regional dan global yang mendukung pelestarian hutan perlu diteruskan.
Zhang dan Gui (2020) dalam kajiannya terkait investasi hijau dan pertumbuhan ekonomi di China mencatat investasi hijau (dalam hal ini pengelolaan limbah) berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi China. Setiap kenaikan 1 persen dalam pengelolaan limbah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,41 persen. Temuan yang sama diafirmasi oleh Pimonenko, dkk (2021) yang menemukan bahwa di Uni Eropa, pertumbuhan investasi hijau sebesar 1 persen meningkatkan PDB sebesar 0,05 persen.
Temuan tersebut menjadi klarifikasi akademik yang jernih dalam menyikapi skeptisme atas investasi yang pro-lingkungan. Kadangkala, segregasi dari pertumbuhan dan keberlanjutan lingkungan diterima sebagai postulat absolut. Padahal, dengan perkembangan teknologi, investasi tidak harus selamanya menjadi tertuding utama kerusakan lingkungan.
Tantangan bagi Indonesia
Sebagai negara yang berhasrat memacu pertumbuhan, logika investasi terjebak perdebatan panjang. Ada sebagian kalangan yang menganggap investasi dan pertumbuhan adalah dua koin yang berbeda. Ada pula yang memandang keduanya bagai gambar di keping logam yang sama. Perbedaan paradigma inilah yang harus diurai terlebih dahulu agar tidak terjerumus pada kebijakan yang mengorbankan masa depan. Dengan demikian, capaian realisasi investasi perlu ditilik dengan analisis yang lebih mendalam. Ini penting agar investasi tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan.
Secara sektoral, pertambangan menempati urutan ke-3 terbesar dalam capaian investasi di kuartal pertama 2025, dengan nilai Rp48,6 triliun atau 10,4 persen dari total realisasi. Masih besarnya proporsi pertambangan mencerminkan investasi belum sepenuhnya ramah lingkungan. Hal ini beralasan karena pertambangan kerapkali mendistorsi kualitas lingkungan di area terdampak. Di sisi lain, dengan proporsi industri logam dan barang logam yang mencatat realisasi tertinggi, yakni Rp67,3 triliun atau 14,5 persen, komitmen investasi hijau perlu lebih ditegakkan.
Logikanya mudah ditebak: industri pengolahan masih sangat bertumpu pada energi fosil, 70 persennya berasal dari batubara (IESR, 2024). Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih fokus dalam melakukan diversifikasi dan transisi energi. Kita tidak lagi mengeja perubahan iklim, melainkan tersandera dalam krisis iklim. Indikatornya sederhana, terjadi kenaikan permukaan laut di utara Pulau Jawa, serta terancamnya daratan kecil di berbagai wilayah nusantara.
Apa yang Mesti Dilakukan?
Mitigasi krisis iklim bukan perkara mudah. Ini membutuhkan kolaborasi global yang berdampak. Jalan terbaik adalah melaksanakan amanat Kesepakatan Paris dengan memperluas kepemilikan, memobilisasi pembiayaan, serta menghasilkan manfaat bagi ekonomi dan masyarakat. OECD (2025) merekomendasikan lima langkah strategis. Pertama, kolaborasi menyeluruh semua satuan pemerintahan, baik berupa dukungan operasional maupun pembiayaan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi terarah pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan kebijakan fiskal yang pro-lingkungan.
Kedua, komitmen Kesepakatan Paris harus terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional dan daerah. Dengan begitu, rencana kebijakan mengarusutamakan pengurangan gas rumah kaca dan emisi karbon. Ketiga, sinergi dengan dunia usaha dalam mewujudkan investasi hijau. Hal ini meniscayakan jaminan hukum, deregulasi, dan insentif ekonomi yang menarik.
Keempat, kerjasama dan penguatan lembaga keuangan melalui peningkatan kapasitas dan integrasi risiko iklim ke dalam regulasi keuangan, serta kemudahan akses pembiayaan dari lembaga pembangunan global. Kelima, pelibatan semua pihak yang terdampak dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi perubahan iklim. Dengan begitu, transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat berjalan adil dan diterima oleh masyarakat.
Krisis iklim bukan mitos, tapi nyata. Ia tidak lagi diskursif, namun aktual. Perlu langkah nyata dalam memitigasi krisis kehidupan. “Yang merawat alam, akan dirawat oleh zaman,” investasi hijau adalah pijakan bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Arifuddin Hamid
Direktur Eksekutif Prolog Initiatives, Alumnus Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan FEB UI
Dimuat Katadata, 25 Juni 2025