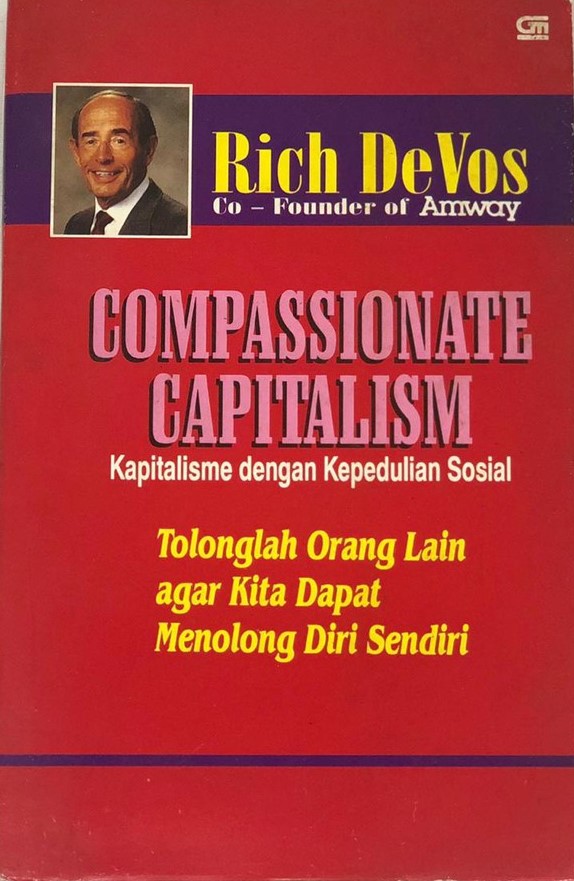Belum lagi optimal meredam derap laju korupsi yang tidak berlorong, nalar pemberantasan korupsi berlajur simpang. Penangkapan oknum lembaga parlemen, birokrasi, bahkan terakhir lembaga yustisi yang kerap berujung pada sengketa kelembagaan nyaris melumpuhkan KPK. Kejadian ini bahkan menjadi preseden kelembagaan di sepanjang kinerja pemberantasan korupsi. Padahal pada tahun inilah introspeksi dan kecemasan sekaligus perlu dikemukakan. Introspeksi sebab dari data yang dilansir KPK (31 Januari 2016), semua jenis tindak penanganan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, dan eksekusi tidak mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam lokus profesi pelaku, terjadi perluasan rentang pelaku dengan semakin banyaknya pelaku swasta yang dijerat, bahkan secara kumulatif terbanyak sampai awal tahun 2016 (130 orang). Fakta ini pula yang menuntut kita semua merasa cemas, sebab narasi pemberantasan korupsi semakin memasuki labirin tak berujung.
Belum lagi optimal meredam derap laju korupsi yang tidak berlorong, nalar pemberantasan korupsi berlajur simpang. Penangkapan oknum lembaga parlemen, birokrasi, bahkan terakhir lembaga yustisi yang kerap berujung pada sengketa kelembagaan nyaris melumpuhkan KPK. Kejadian ini bahkan menjadi preseden kelembagaan di sepanjang kinerja pemberantasan korupsi. Padahal pada tahun inilah introspeksi dan kecemasan sekaligus perlu dikemukakan. Introspeksi sebab dari data yang dilansir KPK (31 Januari 2016), semua jenis tindak penanganan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, dan eksekusi tidak mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam lokus profesi pelaku, terjadi perluasan rentang pelaku dengan semakin banyaknya pelaku swasta yang dijerat, bahkan secara kumulatif terbanyak sampai awal tahun 2016 (130 orang). Fakta ini pula yang menuntut kita semua merasa cemas, sebab narasi pemberantasan korupsi semakin memasuki labirin tak berujung.
Dramatik
Semenjak kemunculannya pada tahun 2004, KPK telah mengisi ruang kosong pemberantasan korupsi. Bahkan dengan derap mengharu biru dan hasil yang begitu luar biasa. Sepanjang satu dekade ini, jumlah kasus yang ditangani dan koruptor yang mengisi jeruji semakin menunjukkan grafik menaik. Fakta ini sekilas memekarkan harapan bagi cita negeri bebas korupsi. Namun pertanyaannya, apakah objektifikasi itu adalah realitas yang seadanya atau realitas fatamorganik belaka? Jawaban menjadi semakin penting mengingat hampir semua lembaga negara tidak tersisa dari perilaku koruptif, selain KPK sendiri yang dipandang masih kredibel dan berintegritas. Atau bahkan semoga maknanya tidak mengalami konvergensi, bahwa konsistensitas justru menggambarkan epos kegagalan.
Klaim objektif inilah yang menegaskan otoritas KPK sebagai lembaga super (superbody organ). Sampai muncul simpulan kerja KPK untuk memberi efek jera—berfokus pada penjeratan pelaku. Namun pertanyaan perlu diselipkan pada riuh ciduk kerja KPK, apakah efek jera mesti diukur dari jumlah pelaku yang berhasil ditindak? Pertanyaan ini semakin perlu ketika dihadapkan pada fakta statistik yang menambah deret jumlah pelaku. Sementara indikator standar menilai “bebas korupsi” sendiri masih menjadi perdebatan diskursif di berbagai pihak, menggantungkan semata cita antikorupsi pada KPK adalah berpotensi menjadi gagasan ahistoris.
Dalam rezim perundangan kita, banyak pihak telah menegaskan preferensi fungsi preventif KPK ketimbang laku represif. Konsiderans menimbang UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) secara eksplisit telah menegaskan bahwa urgensi keberadaan KPK didasarkan pada ketidakefektifan dan inefisiensi lembaga negara yang ada. Namun apabila membaca cermat rumusan tersebut, KPK sejatinya dibentuk dalam hal optimalisasi kelembagaan dengan sebaran kerja yang berefek sistemik. Dengan kata lain, KPK tidak dibentuk sebagai institusi pengganti, melainkan pemicu bagi optimalisasi institusi inti: kepolisian dan kejaksaan.
Dari sisi legalistik, konsiderans menimbang adalah landasan filosofis dan sosiologis bagi keberlakuan suatu peraturan hukum. Oleh karenanya kita akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana wujud strategi yang dimaksud oleh undang-undang, atau dalam lanskap lebih luas, yang berkeadilan bagi publik? Konteks pertanyaan inilah yang relevan untuk menanggapi derap laju KPK hari ini yang lebih menitikberatkan pada pencidukan terduga korupsi. Dalam data yang dilansir awal tahun 2016, KPK telah menjerat 525 pelaku. Besaran angka ini adalah angka antara yang berpotensi makin banyak dalam tahun-tahun mendatang.
Oleh karenanya, fakta statistik yang kerap menempatkan Indonesia pada negara darurat korupsi perlu ditelaah dengan perspektif multi. Misalnya dalam indeks persepsi korupsi (IPK) oleh Transparency International atau indeks resiko korupsi (IRK) oleh lembaga Maplecroft yang tidak menunjukkan perkembangan signifikan bagi kenaikan peringkat Indonesia, sejatinya perlu dipandang dari sudut paradoks (argumentum a contrario) dan karenanya determinis belaka. Determinisme ini berangkat dari desain logika kelembagaan KPK yang memang tidak bersifat sistemik dan berkesinambungan. Secara kasat hal ini pulalah mengapa muncul klausula “ad hoc,” yang artinya sementara atau mengurus hal-hal mendesak tertentu.
Dalam IPK misalnya, persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi mengalami surplus yang konsisten. Pada tahun 2004, IPK Indonesia berada pada angka 20, terus menaik hingga mencapai angka 36 pada tahun 2015. Namun kenaikan ini pun tidak signifikan—hanya naik 2 angka dari tahun 2014—sehingga persepsi korupsi pun masih dapat dikategorikan endemik. Bahkan Maplecroft (2014) secara khusus menyorot bahwa hampir semua sektor bisnis di Indonesia menghadapi resiko korupsi dalam tingkat yang sangat parah (extremely high risk).
Efek jera ini dapat pula ditafsir operasionalistik. Bahwa KPK hanya mengurus perilaku koruptif dalam lokus empirik, pergerakannya berlandas pada fakta lapangan atas maraknya kasus yang terjadi. Implikasinya adalah ramainya pencidukan para terduga. KPK yang berhasil adalah KPK yang menangkap banyak tertuduh! Persis logika inilah yang juga menimbulkan paradoks baru: kuantitas mengalami pemaknaan yang berganda. Di satu sisi, besaran yang tertangkap adalah wujud berfungsinya lembaga ini. Sementara di sisi lainnya, justru memancing pertanyaan lanjutan: sampai kapan korupsi berakhir?
Dengan sendirinya, lokus bahasan mengenai efek jera perlu dilekatkan pada faktorial motif dan karakteristik perilaku koruptif. Faktorial ini menjelaskan relasi konseptual antara tindakan dengan resiko. Terkait motif tindak pidana tersebut, Gary Becker (1968) menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana bukan karena motif dasar yang berbeda dengan orang lain, melainkan adanya hitungan rasional dan faktor biaya. Analisis Becker inilah yang dikenal dengan teori rasional dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian, seorang koruptor melakukan korupsi atas dasar kesadaran yang berlandas pada keuntungan ekonomi yang akan didapatkannya. Hal serupa juga disampaikan oleh Piliavin, dkk (1986) bahwa terdapat keterkaitan antara peluang dan keuntungan dari model pilihan rasional, meskipun tidak ada relevansinya dengan resiko.
Rasionalitas bertindak inilah yang menjadikan diktum perampasan aset merasa perlu dikodifikasi, hingga secara faktual terbitnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menegaskan pola penegakan hukum yang lebih progresif dan responsif publik. Sejatinya dengan adanya klausula “pembuktian terbalik/pembalikan beban pembuktian (Pasal 77 UU TPPU)” dan “perampasan aset (Pasal 67 UU TPPU jo Pasal 18 UU Tipikor),” kebocoran keuangan negara dapat ditambal dengan signifikan.
Namun dengan hanya (dapat) memenjarakan koruptor tanpa mampu memulihkan aset negara secara optimal dan berhasil guna, semoga KPK tidak sedang mewartakan narasi melodramatik—gemuruh padahal tak riuh.
Arifuddin Hamid
Peneliti Partnership for Strategic Initiatives, Mahasiswa Pascasarjana UI
Opini dimuat Harian Suara Karya, 12 Mei 2016