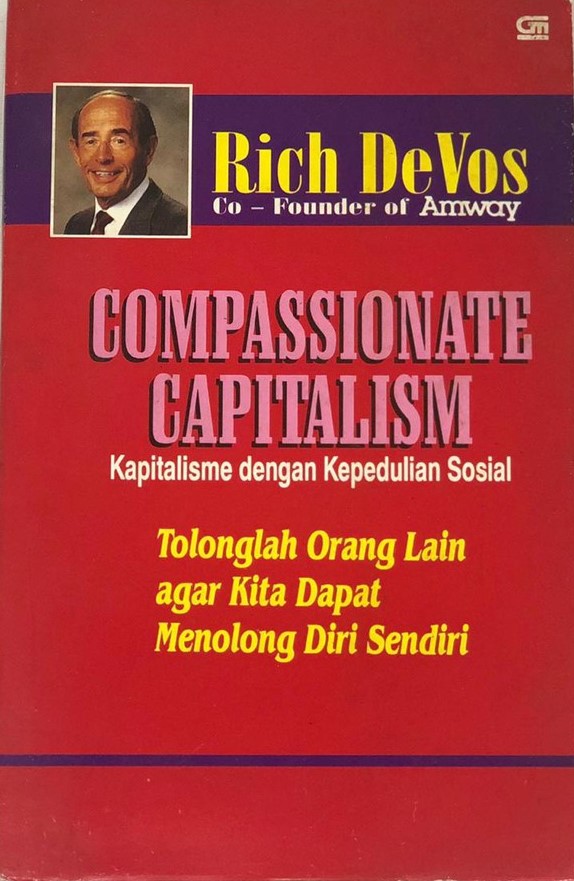Mahalnya biaya penyelenggaraan pilgub adalah sebentuk anomali politik. Dana operasional penyelenggaraan pilgub 2013 sebesar Rp8 miliar yang berasal dari APBD tahun anggaran 2012 (KPUD NTB, 6/7/12) dirasa masih terlalu kecil. Bahwa setidaknya, sebagaimana dilansir Harian Kompas (11/04/12), untuk menjamin kualitas demokrasi, KPUD NTB membutuhkan biaya sebesar Rp10,5 miliar.
Mahalnya biaya penyelenggaraan pilgub adalah sebentuk anomali politik. Dana operasional penyelenggaraan pilgub 2013 sebesar Rp8 miliar yang berasal dari APBD tahun anggaran 2012 (KPUD NTB, 6/7/12) dirasa masih terlalu kecil. Bahwa setidaknya, sebagaimana dilansir Harian Kompas (11/04/12), untuk menjamin kualitas demokrasi, KPUD NTB membutuhkan biaya sebesar Rp10,5 miliar.
Besaran di atas adalah biaya antara yang belum seutuhnya menggambarkan biaya pilgub. Bahwa masih ada biaya lain yang seadanya spekulatif dan determinis: biaya sosial-politik. Spekulatif sebab tidak ada gambaran pasti mengenai besarannya. Dan ia selalu determinis- bergantung konteks: populasi, budaya politik, dan posibilitas kompetisi.
Pilgub selalu menampilkan teater bersambung, sebelum dan sesudah pemilihan. Epos demokrasi dimulai tatkala kandidasi menemukan ruang politiknya dalam interaksi keseharian. Para kandidat mulai melakukan persuasi dengan sekian metode untuk menggiring calon pemilih. Permainan wacana dengan libatan banyak instrumen: organisasi, komunitas, media.
Bahwa biaya sosial-politik juga tidak sekadar berbicara kuantitas material, namun biaya nonmateri yang berujung pada kerugian material itu sendiri. Fragmentasi sosial yang terjadi di tengah nuansa politik yang memanas pada ujungnya berimplikasi pada memudarnya kolektivitas membangun daerah. Sebab rakyat terlampau disibukkan dengan aktivitas politik belaka, nalar akan dibungkan oleh hasrat dan emosi.
Pilgub berbiaya tinggi memang sebentuk kenicayaan demokratik. Sambungan episode pascapemilihan bahkan menampilkan teater lebih tragis, termasuk nyawa sebagai taruhannya. Fakta untuk itu telah berkelindan dengan cerita demokrasi itu sendiri.
Bedah Pilgub
Demokrasi perlu ditilik dari dua perspektif: politik dan hukum. Dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2013 (pilgub) adalah objek bedahnya.
Demokrasi juga bernalar ganda: kualitatif, sekaligus kuantitatif. Tentang kandidasi, konsep kepemimpinan, dan peluang angka.
Secara politik, pilgub adalah instrumentasi sekaligus manifestasi demokrasi.
Dengan pilgub, pimpinan pemerintahan provinsi dipilih oleh khalayak, guna mengagregasi kepentingan publik dalam format kebijakan. Pilgub adalah alat, cara, dan metode memilih siapa yang laik untuk mengejawantah kebaikan bersama (bonum commune). Pilgub adalah bentuk lain dari ‘proseduralisasi demokrasi.’ Beradab tidaknya pilgub menunjukkan bagaimana kualitas demokrasi.
Selanjutnya sebagai manifestasi demokrasi, pilgub adalah demokrasi itu sendiri. Pilgub adalah tujuan. Dengannya, demokrasi dimaknai dengan praksis kedaulatan rakyat. Pemimpin terpilih mendapat mandat untuk mewakili rakyat dalam perbuatan politik. Bahwa harfiah ‘kekuasaan rakyat’ adalah juga kuasa melibatkan diri secara langsung dalam saluran demokrasi yang tersedia.
Namun demikian, pilgub tidak boleh hanya berhenti pada wilayah doktrin. Operasionalisasi atasnya perlu libatan yuridik sebagai panduan praktis berdemokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi tidak lagi sekadar bermakna konseptual, filsafati, namun mewujud menjadi kebijakan formal.
Nomokratisasi demokrasi menjadikan demokrasi menjadi variabel dependen secara operasional. Demokrasi akan terniscaya menjadi diktum positivistik. Positivisme ini yang kemudian membuat direktisasi metodologis pilgub terjebak polemik. Teorema vis a vis, antara kualitas kedaulatan dengan kompetensi yang terdaulati.
Klausula Pasal 56 ayat (1) UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: demokrasi berasas langsung, paradoks dengan kewenangan gubernur terpilih. Euforia demokrasi pascareformasi menitikberatkan otonomi pada tingkatan pemerintah kabupaten/kota. Bukan pada pemerintah provinsi.
Tentang hal tersebut, diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 32/2004 bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
Lebih lanjut melalui PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa karena jabatannya, gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Praktis gubernur bertanggung jawab kepada presiden (ayat 2).
Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaran dekonsentrasi dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga menjelaskan kuasa dua tingkat yang diterima gubernur. Artinya, kewenangan gubernur adalah kewenangan kementerian/lembaga yang dikuasakan kepadanya. Klausula ini yang kemudian diartikan secara politis dengan rencana revisi mekanisme elektoral dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 12/2008.
Karenanya, telaah perspektif antara politik sebagai filsafat dan hukum sebagai teorema operasional perlu ditambahi oleh kajian tentang efektivitas daripada proseduralistik pilgub dan solusi atasnya.
Mencari Instrumen
Polemik wajah ganda pilgub mesti dicari ‘jalan tengah’-nya. Hal ini agar pilgub tidak jatuh ke salah satu titik ekstrim: ilusifitas demokratis atau positivisasi aksiomatik. Keberentahan politis atau limitasi aspiratik.
Sebagaimana disinggung di awal, pilgub yang membutuhkan biaya besar perlu dijadikan pijakan diskursus dalam upaya mencari dan menemukan solusi idealnya. Sebagai realitas politik sekaligus hukum, pilgub bukan lagi bersoal pada pembongkaran konsepsinya. Melainkan pada bagaimana diketengahkan rumusan ‘pendamai’ yang merangkul kedua perspektif.
Dalam konteks demikian, penulis memberi tawaran strategis berupa instrumentasi kalkulasi kuantitatif dalam menilai siapa-siapa saja kandidat yang akan bertarung. Strategi modern politik telah merumuskan metodologi seperti apa yang mampu memberi gambaran mengenai hakikat kandidasi.
Bahwa politik elektoral hari-hari ini tidak lagi berdimensi imajinatif, semu, dan berdasar keyakinan kasat semata. Elektoralisasi telah mewujud dalam hitungan angka-angka simulatif yang memiliki kebenaran empiris. Metode survei (survey method) telah banyak terbukti menjadi indikator ampuh dalam menilai calon yang laik atau tidak.
Hasil eksplorasi simulatif tersebut dapat dijadikan landasan, yang memiliki raihan tinggi yang semestinya diberikan panggung politik. Sebaliknya yang rendah perlu legowo untuk secara teratur mundur dari percaturan.
Di level stratejik, metode ini dapat diinstitusionalisasi oleh masyarakat di yurisdiksi bersangkutan. Atau bahkan institusi serupa yang berada di seluar areal. Penulis merasa, lembaga pemeringkat elektoral di negeri ini memiliki kualitas untuk itu. Sementara dalam tataran taktisnya, data dan angka yang tersaji dapat dihubungkan dengan jejak rekam para kandidat.
Penulis juga yakin, atas hasil survei yang ada, masyarakat NTB akan mampu untuk memilah siapa-siapa saja yang dalam riil politik memiliki kualitas kepemimpinan. Bahwa yang tertinggi belum tentu deskripsi akan kualitas, masih serba mungkin. Pun demikian yang rendah. Namun setidaknya, dari fakta elektoral yang ada, survei telah banyak menyajikan kebenaran faktual dalam derap kompetisi politik.
Pada akhirnya, pembatasan jumlah kandidat akan menjadi teorema politik elektoral dalam menjaring siapa dan berapa kandidat yang perlu bertarung dalam pilgub NTB 2013. Kalau dua pasang calon saja akan menjadi pertarungan ideal, mengapa tidak?
Arifuddin Hamid
Alumnus Fakultas Hukum UI
Pernah dimuat Suara NTB, 19/10/2012